18.7.06
Negeri Kulit -halaman dua-
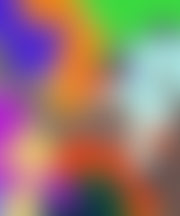 Fre memang selalu begitu, aku sulit membedakan air mukanya saat sedih, bingung, atau gembira. Hanya kemarahan saja yang sedikit lain, biasanya mata Fre mengecil, membentuk garis-garis lengkung di sudut. Kulitnya yang abu-abu menjadi kehitaman.
Fre memang selalu begitu, aku sulit membedakan air mukanya saat sedih, bingung, atau gembira. Hanya kemarahan saja yang sedikit lain, biasanya mata Fre mengecil, membentuk garis-garis lengkung di sudut. Kulitnya yang abu-abu menjadi kehitaman.
"Lihat, ini bekas lukanya, aku belah pakai pisau pemberianmu. Itu lho, pisau yang katamu tidak bisa karatan," Fre tidak memandangku, hanya memperhatikan bekas lukanya yang masih basah, sambil sesekali menyentuhnya dan meringis. "Semalam aku melakukannya di kamar, lewat tengah malam. Hampir saja pingsan," tawanya berderai-derai. Aku masih diam saja sambil menarik kulit dahi di antara alis keras-keras. "Biru, warnanya biru, itu artinya aku kekurangan warna kuning!" tawanya tak berhenti. Aku tetap tidak tahu apakah dia bersedih, gembira atau bingung.
"Fre, aku beda dari mereka, kau juga beda dari mereka, dan dari aku," ujarku tanpa berharap dijawab. "Ya iya, ungu beda dari kuning, dan biru beda dari kuning juga dari ungu," timpal Fre. Otakku sibuk membayangkan apa yang akan terjadi dengan kami jika Kulit Kuning atau Kulit Abu-abu tahu. Jelas kami bukan bagian dari mereka, bahkan sejak lahir. "Kau tahu kan Fre, mereka tidak suka perbedaan, maunya sama semua, seragam, macam baju sekolah," gumamku perlahan. Fre tak acuh. Dia menyalakan cerutu, oleh-oleh seorang kawan yang minggu lalu berkelana ke sudut negeri paling timur. "Rasanya aneh..." gerutu Fre tanpa berhenti menghisapnya."Fre? kau dengar aku tidak sih?" teriakku. "Iya, aku tahu, tidak usah kau bilang aku sudah tahu," jawabnya sembari menyodorkan cerutu untuk kucoba. Aku menolak.
Rencana aku dan Fre untuk migrasi ke planet tetangga tak mungkin dirobohkan. Dan memang belum ada yang tahu hingga sekarang, jadi siapa yang akan menjegal? Planet Seule, rumah impianku, yang ternyata juga diidamkan Fre. Jaraknya tidak jauh dari planet ini, hanya terhalang satu planet saja. Namun tidak mudah menuju ke sana. Jika planet lain bisa ditempuh dalam satu atau dua hari saja dengan pesawat biasa, Seule meminta jauh lebih banyak: keinginan kuat, keyakinan, pemikiran terbuka, pengetahuan teknologi terkini, keberuntungan dan kata kunci untuk mengakses salah satu pintu rahasia yang jumlahnya hanya lima serta begitu tersembunyi. Konon beratus tahun lalu, ada penduduk negeri kami yang berhasil menembus pintu itu, salah satunya kakek buyutku.
Kabar Kakek Buyut tidak pernah terdengar lagi. Menurut rumor, dia kerasan tinggal di Seule. Ah entahlah... Tapi gosip itu memang masuk akal juga, karena (sst... please jangan bilang-bilang!) salah satu pintu rahasia itu ada di halaman belakang rumahku yang warisan turun temurun, di bawah kandang kucing.
Si Cantel, anak kucing entah generasi keberapa, yang bulunya juga kuning, mirip kulitku, pernah enggan keluar dari kandangnya. Susah payah aku merogoh dan memaksanya keluar. Nihil, dia makin membandel. Badannya kian kurus dan mukanya kuyu tidak karuan. Setelah beberapa hari, akhirnya aku goyang-goyangkan kandangnya agar dia takut. Bukannya berhasil, kandangnya rusak dan terguling. Saat itulah aku menemukan pintu rahasia.
Kotak seukuran lebar badan orang dewasa, berkilat-kilat hampir transparan. Mirip genangan air di atas tanah yang tersentuh cahaya matahari. Ada tulisan kecil di sudut kanannya: "Seule, Enter Password:". Aku sempat bergetar hebat. Sudah lama aku dapat kabar tentang pintu rahasia ini dari angin yang kebetulan mampir. Pernah juga burung membisikkan rumor yang sama, lengkap dengan gambaran rupa. Persis!
Planet Seule terbentang di benakku. Tempat indah yang langitnya jarang berawan. Di sana warna-warna berdampingan sempurna. Tidak ada satupun yang merasa lebih atau perlu berbangga. Penduduknya giat bekerja, rajin berdoa. Mereka saling menyapa tanpa menerka, apalagi menuduh. Bagi mereka, mempersoalkan urusan orang lain, meributkan soal warna, atau menghakimi bentuk wajah adalah tidak masuk akal. Mereka tidak lagi punya kemampuan itu, sejak lama mati. Mereka tidak pernah ingat lagi apa warna kulitnya, apalagi jantung. Konon, mereka hanya punya sedikit saja perasaan, sisanya tinggal logika. Logika bahwa menghargai orang lain, berarti menjaga kenyamanan sendiri. Logika bahwa dengan memelihara alam, berarti menyelamatkan hidup seluruh planet.
Cerita tentang Seule banyak tersebar di dahan-dahan, juga dinding batu. Komunitas fotografer lepas ada yang pernah memuat gambar-gambarnya di tempat-tempat ramai. Aku tidak tahu apakah Seule memang benar begitu, aku belum pernah bertemu dengan orang yang mengaku berhasil menjejakkan kaki di sana. Bagiku, mempercayai keindahan tidak merugi.
Ada yang aneh. Bukankah seharusnya planet kami justru lebih selamat dan lebih nyaman? Sedari lahir kami diajari kelembutan, dicekoki pandangan tentang hidup, tepo seliro, gotong royong dan berbagi kasih sayang. Bukankah seharusnya planet kami terjauh dari perang ego, adu jotos dan hantam kromo? Apalagi negeriku yang mengaku berbudaya tinggi dan berhati luhur. Bukankah gambaran di Seule tampak begitu egois? Lalu mengapa mereka mereka yang hidup tenteram dan kami yang jatuh-bangun?
"Aku rasa aku tahu apa yang mestinya aku lakukan," tiba-tiba saja Fre berkata sambil menepuk bahuku. Hampir saja aku terlompat kaget. "Apa Fre? Maksudmu?" lamunanku yang panjang lebar membuat suara Fre berdengung sebagian. Fre tidak peduli, "Aku mau ganti kulit! Aku mau operasi ganti warna kulit jadi kuning!"
Petir menyambar wajahku. Pandangan buram terhalang asap yang tidak bisa kutepis. Badanku menggigil, dingin bukan main. Aku kehilangan keseimbangan.
Gila, bisa mabok bacanya. Udah dulu ah, mau ke atas genteng, menatap Seule, mudah-mudahan masih ada.

Read or Post a Comment
<< Home